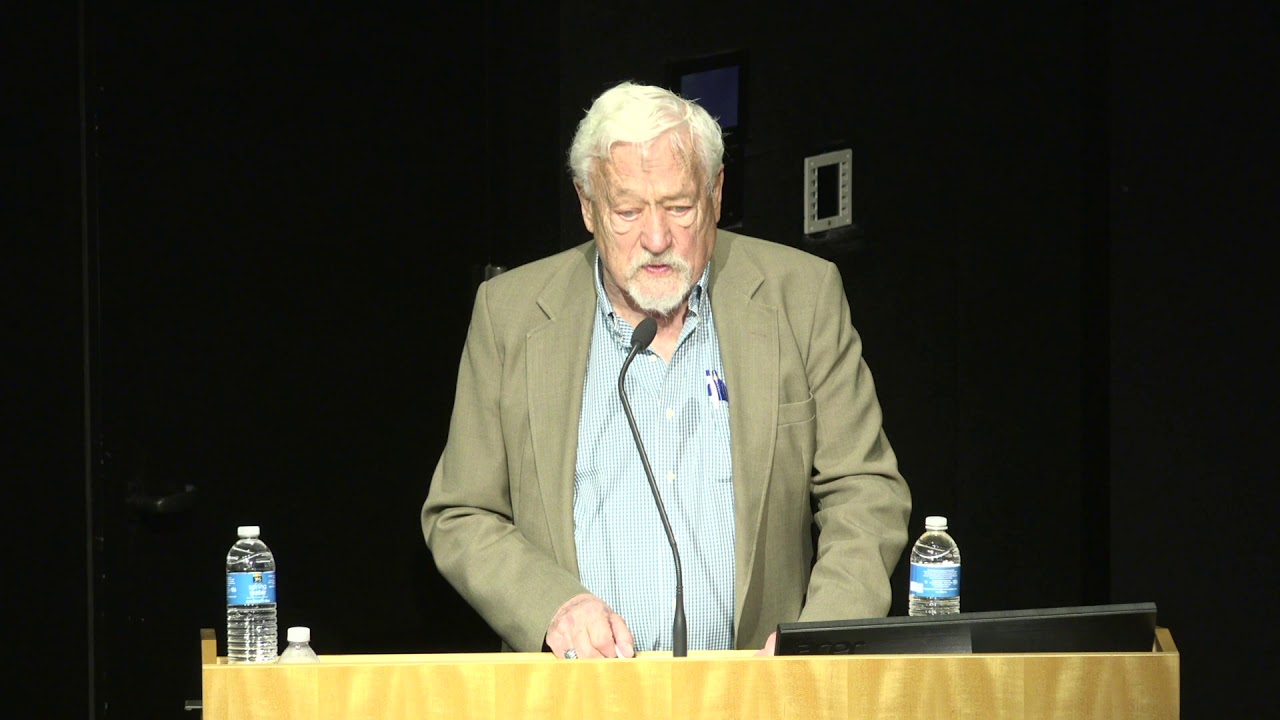Don Ihde pada tahun 2004 menyebarkan keraguan dan harapan. Dengan artikelnya yang berjudul “Telah sampaikah filsafat teknologi? Keadaan Terbaru”.
Ihde mengevaluasi secara kritis keadaan disiplinnya sendiri. Pertanyaan evaluasinya cukup sederhana: Sudah mapankah filsafat teknologi sebagai disiplin?.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ihde membandingkan diskursus filsafat teknologi dengan dua “saudara” sekelahirannya, filsafat ilmu dan sosiologi ilmu.
Berhasilkah Ihde menjawab pertanyaannya?
Sejauh penelusuran Ihde, filsafat teknologi dan filsafat ilmu adalah saudara sezaman.
Mereka lahir di awal abad ke-20 sebagai reaksi atas perkembangan yang pesat dari dua objek tersebut.
Hanya saja, jika filsafat ilmu pada awal diskursusnya cenderung dikuasai oleh tradisi analitik-positivistik, seperti Hempel, Carnap, dkk.,
filsafat teknologi justru adalah anak dari diskursus praxis pragmatisme Amerika Utara, fenomenologi, dan teori kritis Neo-Marxis.
Perbedaan tradisi ini membuat banyak orang salah paham, terutama terkait status kelahiran filsafat teknologi.
Ihde mencontohkan kesalahpahaman ini dalam pernyataan-pernyataan Mario Bunge yang mengatakan bahwa pada tahun 1979 belum ada yang menjadikannya filsafat teknologi isu utama.
Padahal di tahun yang sama, Don Ihde dan Bruno Latour menerbitkan buku sistematis tentang filsafat teknologi.
Kesalahpahaman ini, bagi Ihde, terjadi karena bias yang melingkari filsafat kontinental sebagai filsafat “yang tidak jelas”.
Padahal, diskursus teknologi telah dibahas secara filosofis oleh filsuf-filsuf sekaliber Gassett, Jaspers, Gehlen, dan Heidegger.
Implikasinya, memang, yang membuat Ihde heran, diskursus filsafat ilmu seakan menghilangkan problem-problem teknologis dalam proses keilmuan.
Secara tidak langsung, para filsuf ilmu mengandaikan bahwa teknologi itu netral.
Padahal dalam filsafat teknologi, persoalan tersebut masih diperdebatkan (lih. perdebatan substansialisme, instrumentalisme, teori kritis, dan determinisme teknologi).
Contoh paling krusial adalah karya Laudan yang bagi Ihde seakan mengingatkan kita kepada persoalan lama tentang masalah proposisi dalam teori.
Setelah berkembangnya filsafat teknologi, mulai banyak pemisahan, dan mungkin penggabungan baru antara batas ilmu dan teknologi.
Dari sana dapat dilihat bagaimana sebenarnya hubungan antara ilmu dan teknologi begitu dekat.
Pengaruh teknologi terhadap ilmu terlihat di berbagai aspek, seperti dalam sejarah ilmu (Galileo), penemuan-penemuan fisika terbaru, sikap-sikap teknologis dalam ilmu, hingga masalah keterbatasan subjek ilmuwan.
Jika ingin ditarik pada garis yang cukup jelas, arah perkembangan perdebatan menyempit menjadi dua sisi. Pertama, posisi yang cenderung memisahkan filsafat teknologi dan filsafat ilmu.
Asumsinya dua objek tersebut memang terpisah walaupun saling mempengaruhi. Ilmu memiliki logika sendiri, begitu juga dengan teknologi. Kedua, posisi yang merasa kedua disiplin tersebut tidak dapat dipisah.
Argumen ontologisnya adalah ilmu dan teknologi saling bergantung.
Meskipun begitu, pada satu titik, ada kemungkinan bahwa teknologi dapat menjadi mandiri (autonomous), dan bahkan mempengaruhi gerak logika ilmu.
Dari sini jelas terlihat pengaruh dystopia (takut akan teknologi) tokoh-tokoh kontinental seperti Heidegger, Marcuse, Elul, dan Mumford; cukup kontras dengan pandangan filsuf pragmatis seperti Dewey.
Sketsa awal ini memperlihatkan bagaimana diskursus teknologi sudah cukup berkembang.
Belum lagi jika arah perbincangan diarahkan pada problem ekologi, masa depan teknologi, hubungan dunia-pikiran, etika, dll.
Namun, ternyata, bagi Ihde, ini belum cukup. Ada beberapa keraguan yang membuatnya menahan diri untuk mengatakan bahwa diskurus teknologi telah mapan.
Keraguan Ihde terhadap filsafat teknologi sebagai disiplin yang matang berasal dari respons akademis.
Respons ini menyerang filsafat teknologi lewat dua arah, ruang internal dan eksternal. Menariknya, Ihde, sebagai filsuf teknologi, mengiyakan serangan tersebut.
Apa yang disebut dengan problem internal adalah problem dalam disiplin itu sendiri. Untuk melihatnya, Ihde meminjam kerangka teoretis Kuhn tentang ilmu normal dan pra-paradigma.
Bagi Ihde, berbeda dengan filsafat ilmu dan sosiologi ilmu yang telah memiliki rentang perdebatan yang lama dan kokoh, filsafat teknologi belum memiliki perdebatan tersebut.
Memang, pada beberapa sisi, diskursus filsafat teknologi telah meluas hingga ke berbagai ranah, tetapi jika dibandingkan dengan perdebatan realisme/antirealisme filsafat ilmu, dan chicken epistemology/social constructionist sosiologi ilmu, tentu saja debat dalam filsafat ilmu belum memiliki banyak front pertentangan dalam paradigma dasar (metodologis-ontologis-epistemologi) yang kuat.
Begitu juga dalam ranah eksternal, atau ranah yang memperlihatkan kekuatan suatu disiplin mempertahankan batasnya dengan disiplin lain.
Walaupun filsafat ilmu dan sosiologi ilmu adalah subjek yang interdisiplin, ada garis yang jelas, entah secara paradigmatik atau institusional tentang garis filsafat ilmu yang berurusan dengan masalah meta-teori, dan sosiologi ilmu yang berurusan dengan kondisi sosio-historis ilmu.
Implikasinya, program filsafat ilmu dan sosiologi ilmu dapat berdiri sendiri secara institusional. Dan bagi Ihde, filsafat teknologi belum mendapatkan tempat di institusi pendidikan manapun.
Begitu juga pengaruh filsafat teknologi dengan disiplin lain secara interdisiplin.
Memang banyak yang masuk dalam diskursus filsafat teknologi, namun hal yang sebaliknya masih belum terasa.
Sebagai contoh, dalam filsafat ilmu, posisi pengaruh teknologi (atau hal lain di luar proposisi teoretik) justru lebih dipengaruhi disiplin feminis, sosiologis, dan budaya (kritis).
Filsafat teknologi terus berkembang, dan biarlah berkembang. Masalah yang dilontarkan oleh Ihde tidak berarti Filsafat Teknologi harus tutup.
Mereka hanya butuh waktu dan masalah untuk kemudian disusul dengan masalah baru. Masalah sebenarnya adalah Ihde harus cukup yakin bahwa problem teknologi masih penting untuk diskursus filsafat ilmu tradisi analitik. Untuk itu Ihde memberikan dua masukan.
Pertama adalah tentang imajinasi teknologi. Banyak diskursus analitik sekarang melakukan pembayangan yang “gila” tentang kemungkinan teknologi masa depan dan relasinya dengan ilmu.
Namun fakta mengatakan bahwa banyak imajinasi utopia yang berlebihan tentang teknologi tidak pernah tercapai (lih. helikopter Leonardo Da vinci).
Ada syarat-syarat yang harus tercantum dalam setiap peramalan masa depan teknologi. Walaupun imajinasi ini memiliki asumsi ontologis tertentu, hanya dalam ranah filsafat teknologilah debat ini benar-benar dibuka, agar kita tidak terlalu naif.
Kedua adalah problem epistemologis. Era otak mulai surut. Komputer telah menjelajah banyak penemuan yang secara logika otak jarang ditemukan dan mungkin sulit karena butuh percobaan yang melelahkan (ruang dan waktu).
Persoalannya adalah, secara pengetahuan, teknologi memberikan banyak perlakuan yang menarik entah secara abstrak maupun proposisional terhadap dunia; caranya lewat model dan simulasi komputer.
Dalam posisi ini filsafat teknologi mampu menggambarkan relasi tersembunyi (terutama fenomenologi Ihde) dari kecenderungan dunia model komputer.
Beberapa persoalan metafor pun dapat lahir dari kompleksitas teknologi sekarang.
Sepanjang sejarah, teknologi sering menjelaskan berbagai persoalan filosofis, seperti jam dan pencipta.
Namun dengan kompleksitas teknologi, tentu saja ini dapat membantu para filsuf untuk memetaforkan hal lain tentang dunia dan dengan cara serta kompleksitas yang berbeda.
Bahkan, menurut Ihde, kita dapat memetaforkan kesalahan filsafat lama dengan kompleksitas teknologi sekarang (lih. problem refleksi Descartes dan Locke dengan metafor kamera).
Dua masukan itulah yang bagi Ihde, harus dipertimbangkan untuk kelanjutan filsafat ilmu dalam mempertahankan tradisinya dalam gempur teknologi modern.
Kembali ke pertanyaan awal: apakah filsafat teknologi telah sampai? Jawabannya jelas: belum. Masih banyak persoalan.
Filsafat teknologi, dibanding disiplin lain masih belum mapan. Namun, jangan menyerah.
Filsafat teknologi masih menyimpan harapan. Harapan menemukan paradigma dasar yang kuat (hanya masalah waktu) dan harapan berdialog dengan tradisi lain.
Oleh karena itu, untuk calon filsuf-filsuf teknologi, tetaplah membaca buku. Mari tutup dengan perkataan akhir dari Ihde:
…if philosophy of technology should be the subdiscipline which is most sensistive to materiality, then its practicioners sholud be leading the pack by reading the others who display this sensitivity–of course, it should go the other way, too.
Sumber : https://antinomi.org/masa-depan-relasi-filsafat-ilmu-teknologi/